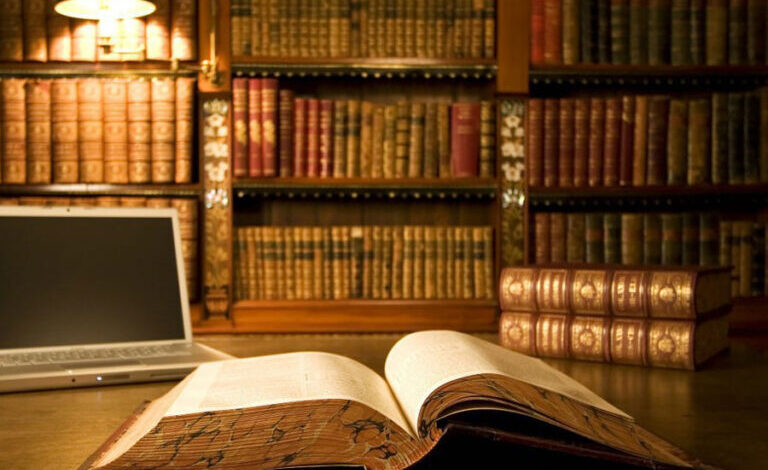
Jaminan Nafkah Istri dan Anak
Dari Aisyah ra. bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata, “Ya Rasulullah, sungguh Abu Sufyan orang yang pelit dan dia tidak memberi aku apa yang mencukupi diriku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari dia dan dia tidak tahu.” Lalu beliau bersabda, “Ambillah apa saja yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan makruf.” (HR al-Bukhari no. 5364, Ahmad no. 25713, Abu Dawud no. 3532, Ibnu Majah no. 2293, an-Nasai di dalam Sunan al-Kubrâ no. 9147, ad-Darimi no. 2305. Ini redaksi al-Bukhari).
Imam al-Bukhari juga mengeluarkan hadis ini pada hadis no. 2211, 5370 dan 7180 dengan redaksi sedikit berbeda.
Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dari jalur Aisyah ra. sebagai berikut:
Hindun binti ‘Utbah istrinya Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw. dan berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang pelit. Dia tidak memberi aku nafkah yang mencukupi diriku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah ada dosa atas diriku dalam hal itu?” Lalu Rasulullah saw. bersabda, “Ambillah dari hartanya dengan makruf apa yang mencukupi dirimu dan anakmu.” (HR Muslim no. 1714).
Menurut para ulama, hadis ini memberikan sejumlah faedah fiqhiyyah. Imam al-Khathabiy (w. 388 H) di dalam Ma’âlim as-Sunan Syarhu Sunan Ibni Dâwud, juga Imam al-Baghawi asy-Syafi’iy (w. 516 H) di dalam Syarhu as-Sunnah, menyatakan bahwa di antara faedah itu: nafkah istri menjadi kewajiban suami dan nafkah anak-anak menjadi kewajiban bapak mereka. Imam al-Baghawi menambahkan bahwa di situ ada ittifâq bayna ahlil ‘ilmi (kesepakatan para ulama) bahwa anak, jika masih kecil atau sudah balig tetapi lemah dan dia kesulitan, maka nafkahnya wajib atas bapaknya yang punya kelapangan. Jika dia telah sampai pada kondisi dapat memperoleh nafkahnya secara mandiri maka gugur kewajiban nafkahnya itu dari bapaknya. Jika nafkah anak-anak adalah wajib maka nafkah kedua orangtua ketika lemah dan kesulitan lebih utama dalam hal kewajibannya atas bapak.
Sebagai kewajiban, nafkah ini harus ditunaikan dengan inisiatif dan kesadaran sendiri. Namun, bagaimana jika suami/bapak itu tidak menunaikan kewajibannya atau menunaikan kewajibannya, tetapi kurang, itulah antara lain yang diatur dalam ketentuan hadis di atas.
Jika suami itu bakhil (pelit), yakni memberi nafkah kepada istri, anak atau orang yang menjadi tanggungannya, dengan kadar yang tidak mencukupi, maka istri boleh mengambil nafkahnya sendiri dari harta suaminya itu, meski tanpa izin dan sepengetahuannya. Hal itu sesuai dengan makna lahiriah dari hadis di atas.
Al-Qurthubi, yang dikutip oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) di dalam Fathu a-Bârî, menyatakan bahwa perintah Rasul saw. kepada Hindun, “khudzî (Ambillah).” adalah perintah mubah. Dalilnya adalah sabda beliau, “lâ haraja (tidak ada dosa)”. (Dalam riwayat lain “lâ junâha (tiada dosa)”.
Menurut Imam Ibnu Barththal (w. 449 H) di dalam Syarhu Shahîh al-Bukhârî li Ibni Baththâl, boleh bagi seseorang untuk mengambil sesuatu dari harta orang yang menghalangi haknya atau menzalimi dirinya dengan kadar hartanya yang ada pada dia. Tidak ada dosa dalam hal itu. Sebabnya, Nabi saw. membolehkan Hindun mengambil dari harta suaminya dengan makruf.
Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam Syarhu Shahîh Muslim menyatakan, “Orang yang punya hak harta yang wajib ditunaikan oleh orang lain, sementara dia tidak mampu mendapatkan haknya itu sepenuhnya, maka boleh dia mengambil dari harta orang lain itu tanpa izinnya sesuai dengan kadar haknya. Ini adalah mazhab kami.”
Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani di dalam An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, jika seseorang itu bakhil (pelit) terhadap orang yang nafkahnya menjadi kewajiban dia, maka orang yang memiliki hak nafkah itu boleh mengambil dari harta seseorang itu dalam kadar kecukupan mereka secara makruf. Dalilnya adalah hadis di atas. Dalam hadis itu, Rasul saw. mengizinkan Hindun mengambil sendiri hak nafkahnya dari suaminya, Abu Sufyan, tanpa sepengetahuan dirinya saat suaminya itu tidak memberi dirinya nafkah. Sebabnya, memberi nafkah itu adalah fardhu bagi suaminya itu. Qadhi harus menetapkan nafkah ini untuk sang istri.
Terkait kadarnya, Imam an-Nawawi menyatakan bahwa nafkah itu dihitung kadarnya (muqaddarah) dengan kecukupan (al-kifâyah), bukan dengan jumlah mud (kuantitas).
Al-Qurthubi, yang dikutip oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) di dalam Fathu a-Bârî, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bi al-ma’rûf (secara makruf)” adalah sesuai kadar yang berdasarkan adat kebiasaan bahwa itu cukup (al-kifâyah).
Imam Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) di dalam Fathu al-Bârî, di dalamnya ada ketentuan kewajiban nafkah istri, yang dihitung kadarnya (muqaddarah) dengan kecukupan (al-kifâyah). Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
Hanya saja, kecukupan itu tetap harus memperhatikan kemampuan suami. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kadar kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan kepada dirinya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar rezeki yang Allah berikan kepada dirinya (QS ath-Thalaq [65]: 7).
Menurut pengarang Al-Hidâyah, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, penetapan kadar (taqdîr) nafkah itu dengan memperhatikan kondisi suami dan istri sekaligus. Hujjah atas hal ini adalah dengan menggabungkan firman Allah QS ath-Thalaq [65]: 7 ke hadis ini.
Syamsuddin al-Asyuthiy asy-Syafi’iy (w. 880 H) di dalam Jawâhir al-‘Uqûd menyatakan, “Para imam sepakat atas kewajiban nafkah untuk orang yang nafkahnya menjadi tanggungan seperti istri, bapak dan anak kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah isteri, apakah dihitung kadarnya berdasarkan ketentuan syariah atau dengan memperhatikan kondisi suami-istri. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berkata; diperhatikan kondisi suami-istri.”
Ini adalah bagian dari mekanisme jaminan atas nafkah isteri dan anak. Menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam Syarhu Shahîh Muslim, seorang wanita punya pintu masuk dalam jaminan (kafâlah) nafkah anak-anaknya dan belanja atas mereka dari harta bapak mereka. Imam an-Nawawi berkata, “Ashhâb kami berkata: Jika bapak enggan memberikan infak (pembelanjaan) atas anak kecil atau dia tidak ada (ghâ’ib) maka Qadhi mengizinkan ibu dari anak-anak itu untuk mengambil dari harta bapaknya, atau berutang atas nama bapaknya, dan membelanjakan hartanya itu untuk anak kecil itu dengan syarat si ibu memang layak untuk melakukan demikian.”
Kebolehan istri membelanjakan harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya, tetapi juga untuk keluarga suaminya yang nafkahnya menjadi tanggungan/kewajiban suaminya itu. Hal itu dinyatakan dalam redaksi lainnya dari hadis di atas. Aisyah ra. menuturkan bahwa Hindun berkata kepada Rasulullah saw.:
“Ya Rasulullah, sungguh Abu Sufyan orang yang menahan (harta yakni pelit). Apakah ada dosa atasku aku tahan (belanjakan) atas keluarganya dari hartanya tanpa izinnya?” Nabi saw. bersabda, “Tidak ada dosa hal itu atas engkau untuk engkau nafkahkan atas mereka dengan cara yang makruf.” (HR ath-Thabarani di Mu’jam al-Kabîr no. 171).
Jika telah ditetapkan kadar nafkah itu dan diserahkan kepada istri, atau istri itu mengambil dari harta suaminya, maka dia wajib membelanjakan harta itu untuk mereka yang berhak atas nafkah suaminya itu. Imam Taqiyuddin an-Nabhani di dalam An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm menyatakan, “Sebagaimana orang yang punya kewajiban nafkah itu wajib menunaikan kewajibannya maka demikian juga orang yang mengambil nafkah itu wajib menginfakkan (membelanjakan) hartanya dalam apa yang diwajibkan atas si suami itu. Jika diwajibkan nafkah untuk anak-anak, sementara Qadhi memerintahkan agar nafkahnya itu untuk diserahkan kepada orang yang mengasuh anak-anak itu—baik ibu, nenek atau yang lainnya—maka wajib bagi orang yang mengambil nafkah itu untuk menginfakkan (membelanjakan) hartanya itu. Seandainya dia tidak membelanjakan hartanya itu maka Qadhi wajib memaksa dia untuk membelanjakan harta gtersebut.”
Inilah di antara hukum tentang pembelanjaan atas keluarga. Ini sekaligus merupakan bagian dari mekanisme Islam dalam menjamin pemenuhan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok, bagi semua orang.
WalLâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]



