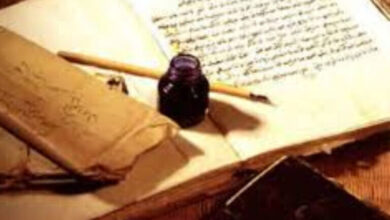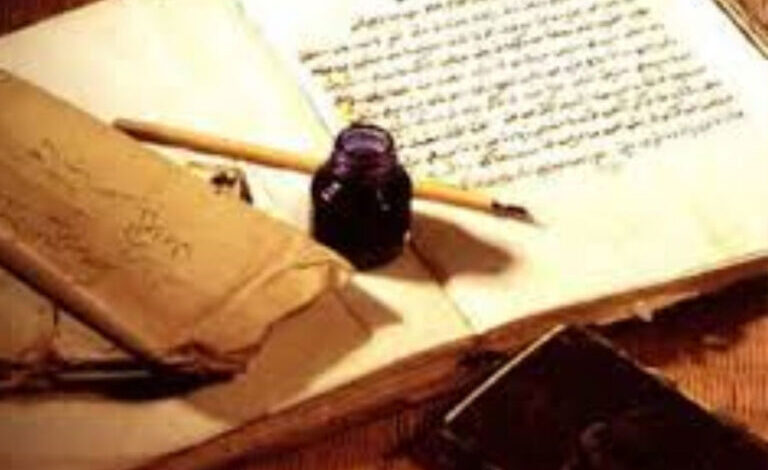
Substansi Nasakh
Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani di dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah Jilid 3: An-Naskhu (nasakh) adalah ibthâlu al-hukmi al-mustafâd min nashsh[in] sâbiq[in] bi nashsh[in] lâhiq[in] (pembatalan hukum yang dipahami dari nas yang lebih dulu dengan nas yang lebih akhir).
Menurut Imam al-Amidi (w. 631) di dalam Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm: An-Naskhu (nasakh) adalah: khithâb asy-Syâri’i al-mâni’i min istimrâri mâ tsabata min hukmi khithâb[in] syar’iyy[in] sâbiq[in] (seruan Asy-Syâri’ yang menghalangi keberlanjutan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan oleh seruan syar’i terdahulu).
Nasakh itu merupakan pencabutan (ar-raf’u) atau pembatalan (al-ibthâl) hukum syariah. Dengan ungkapan lain, nasakh merupakan pemberhentian keberlanjutan pemberlakuan suatu hukum syariah. Hal itu melalui dalil syar’i yang lebih akhir dari dalil yang menentapkan hukum syariah yang di-nasakh.
Syarat Nasakh
Para ulama menjelaskan, nasakh yang syar’i itu harus memenuhi beberapa syarat. Imam an-Nabhani menjelaskan, an-naskhu itu harus memenuhi tiga syarat: Pertama: Hukum yang di-nasakh harus berupa hukum syar’i. Kedua: Dalil yang menunjukkan pencabutan hukum itu harus dalil syar’i yang lebih akhir dari seruan yang di-nasakh hukumnya. Ketiga: Seruan yang diangkat hukumnya tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
Imam al-Amidi (w. 631 H) menyatakan di dalam Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm bahwa syarat an-naskhu syar’i terbagi menjadi syarat yang disepakati dan syarat yang diperselisihkan. Adapun syarat yang disepakati: Pertama, hukum yang di-nasakh adalah hukum syar’i. Kedua, dalil yang menunjukkan hukum itu diangkat (dicabut) adalah dalil syar’i yang lebih akhir dari khithaab yang di-nasakh hukumnya. Ketiga, khithaab yang di-nasakh hukumnya tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
Adapun syarat yang diperselisihkan: Pertama, khithaab yang menunjukkan hukum itu diangkat adalah setelah masuknya waktu yang memungkinkan hukum itu ditaati. Kedua, khithaab yang di-nasakh hukumnya termasuk yang tidak dimasuki pengecualian dan pengkhususan. Ketiga, nasakh al-Quran harus dengan al-Quran dan nasakh as-Sunnah dengan as-Sunnah. Keempat, nas yang me-nasakh dan yang di-nasakh berupa nas yang qath’i. Kelima, kontradiksi yang me-nasakh dengan yang di-nasakh dalam bentuk kontradiksi perintah dengan larangan, al-mudhayyaq dengan al-muwassa’. Keenam, nasakh itu dengan ganti. Semua ini diperselisihkan. Yang benar, perkara-perkara ini (syarat-syarat) tidak mu’tabar.
Nasakh Hukum, Bukan Nasakh Tilâwah
Nasakh itu terjadi atas hukum dan tidak terjadi atas tilâwah (bacaan/redaksi)-nya. Ini adalah pendapat jumhur. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah SWT:
Ayat mana saja yang Kami hapus atau Kami biarkan tidak dihapus, Kami datangkan yang lebih baik dari ayat tersebut atau yang sebanding dengan ayat itu (QS al-Baqarah [2]: 106).
Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, penafsiran ayat ini dengan makna pe-nasakh-an—yakni penggantian ayat dengan ayat lainnya dengan makna secara hakikat—adalah lemah. Sebabnya, itu membuat sifat lebih baik disematkan pada ayat. Padahal satu ayat tidak lebih baik dari ayat lainnya. Yang ada adalah apa yang kembali pada hukum dari ayat yang dicabut untuk kita dan yang ditetapkan atas kita menjadi lebih ringan atau pahalanya lebih besar dari sebagian lainnya. Hukum keteguhan seorang Muslim atas dua orang kafir adalah lebih ringan dari keteguhan atas sepuluh orang kafir. Jadi hukum yang me-nasakh, yaitu keteguhan atas dua orang adalah lebih ringan dari hukum yang di-nasakh, yaitu keteguhan atas sepuluh orang. Hukum puasa Ramadhan lebih berat dari puasa Asyura‘, tetapi pahalanya lebih besar. Jadi kelebihbaikan itu bukan pada ayat itu sendiri, melainkan pada hukum yang dibawa ayat tersebut. Kadang lebih baik dalam bentuk keringanan dan kadang lebih baik pahalanya.
Jadi nasakh itu terjadi atas hukum, bukan atas ayatnya. Artinya, pemaknaan lafal [ آيَةٍ ] itu bukan secara hakikat, tetapi secara majaz, yakni [ حُكْمُ آيَةٍ ] (hukum ayat). Imam Muhammad ibnu Jarir ath-Thabari (w. 310 H) menjelaskan di dalam Jâmi’u al-Bayân fî Ta‘wîl al-Qur‘ân (Tafsîr ath-Thabarî): “Tidak lain yang Allah maksudkan dari firman-Nya [ مانَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ] adalah [ مَا نَنْسَخْ مِنْ حُكْمِ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ]. Namun, karena pihak yang diseru dengan ayat tersebut, maknanya telah menjadi pemahaman pada mereka, maka cukup dengan dalâlah penyebutan lafal [ آيَةٍ ] tanpa penyebutan [ حُكْمُهَا ]. Banyak ayat lainnya yang serupa. Ini seperti firman Allah [ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ] dengan makna [ حُبُّ الْعِجْلَ ] (kecintaan menyembah pada patung anak sapi). Banyak contoh semacam itu.
Jadi takwil (tafsir) ayat tersebut: “Tidaklah Kami mengubah hukum ayat dan Kami ganti, atau Kami biarkan tidak Kami ganti, kecuali Kami datangkan hukum yang lebih baik dari itu untuk kalian, hai kaum Mukmin, atau yang semisal hukumnya dalam keringanan, berat, ganjaran dan pahala.”
Yang menunjukkan hal itu adalah ayat itu sendiri [ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ]. Tidaklah boleh sesuatu dari al-Quran lebih baik dari sesuatu lainnya. Sebabnya, semuanya adalah Kalamullah. Tidak boleh pula dalam sifat Allah dikatakan, sebagiannya lebih afdhal dari sebagian lainnya dan sebagiannya lebih baik dari sebagian lainnya.” Demikian penjelasan Imam ath-Thabari.
Ini sekaligus menegaskan bahwa yang ada adalah nasakh hukum dan tidak ada nasakh tilâwah. Ini karena semua ayat al-Quran ditetapkan dengan dalil qath’i. Yang tidak ditetapkan dengan dalil qath’i, yakni ditetapkan dengan dalil zhanni , tidak dinilai bagian dari al-Quran. Juga tidak terbukti dengan dalil qath’i adanya nasakh tilâwah dari ayat al-Quran. Adanya dalil zhanni berupa hadis ahad yang menyatakan adanya nasakh tilâwah tidak ada nilainya sama sekali. Sebabnya, yang qath’i tidak di-nasakh dengan yang zhanni. Yang qath’i hanya di-nasakh dengan yang qath’i. Tidak dalil qath’i atas nasakh tilâwah. Dengan demikian, tidak ada nasakh tilâwah al-Quran.
Adapun nasakh tilâwah as-Sunnah maka kita tidaklah terkategori ibadah saat membaca as-Sunnah (sebagaimana tilâwah al-Quran). Sebabnya, tilâwah itu sendiri (sebagai ibadah) tidak ada berlaku untuk as-Sunnah. Maka dari itu, tentu saja pembahasan nasakh tilâwah as-Sunnah adalah tidak ada.
Macam-macam Nasakh
Pertama: Nasakh tanpa diganti. Hal itu seperti nasakh atas keharusan bersedekah saat hendak berbicara dengan Rasul (QS al-Mujadilah [58]: 12-13).
Kedua: Nasakh dengan pengganti yang lebih ringan. Itu seperti keteguhan atas sepuluh orang (QS al-Anfal [8]: 65) di-nasakh dengan keteguhan atas dua orang (QS al-Anfal [8]: 66). Juga masa ‘iddah satu tahun untuk wanita yang ditinggal mati suaminya (QS al-Baqarah [2]: 240) di-nasakh menjadi empat bulan sepuluh hari (QS al-Baqarah [2]: 234). Larangan berziarah kubur di-nasakh menjadi boleh. Larangan memakan atau menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari di-nasakh menjadi boleh. Hukuman dibunuh untuk orang yang meminum khamar untuk kali keempat di-nasakh menjadi hukuman cambuk. Jabir bin Abdullah menuturkan, Rasul saw. Bersabda:
“Cambuklah orang yang minum khamar. Jika dia mengulangi minum khamar untuk yang keempat kalinya maka bunuhlah.” Jabir berkata: “Didatangkan kepada beliau setelah itu orang yang meminum khamar untuk yang keempat kalinya. Namun, beliau hanya memukul (mencambuk) dia dan tidak membunuh dirinya.” (HR at-Tirmidzi no. 1444, an-Nasai di Sunan al-Kubra no. 5283, al-Baghawi no. 2604, redaksi at-Tirmidzi).
Imam al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan al-Kubrâ hadis no. 17505 dari jalur Qabishah bin Du’aib.
Ketiga: Nasakh ke pengganti yang semisal. Ini seperti nasakh kefardhuan shalat menghadap ke Baitul Maqdis menjadi fardhu menghadap ke arah Masjidil Haram (QS al-Baqarah [2]: 144).
Keempat: Nasakh ke pengganti yang lebih berat. Ini seperti di awal Islam diwajibkan kurungan di dalam rumah hingga meninggal sebagai hukuman atas zina (QS an-Nisa’ [4]: 15-16). Kemudian hukum ini di-nasakh menjadi hukuman cambuk seratus kali (QS an-Nur [24]: 2). Dari hukuman ini di-takhshîsh dengan hadis bahwa hukuman cambuk itu untuk ghayru muhshan. Untuk yang muhshan hukumannya adalah dirajam.
Contoh lainnya, kewajiban puasa Asyura di-nasakh dengan kefardhuan puasa Ramadhan. Dari Aisyah ra., ia berkata:
Dulu Hari Asyura (10 Muharram) adalah hari orang Quraisy berpuasa pada masa Jahiliah. Rasulullah saw. juga berpuasa Asyura. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa Asyura. Tatkala difardhukan puasa Ramadhan, beliau bersabda, “Siapa yang mau (boleh) berpuasa Asyura dan siapa yang mau (boleh) meninggalkannya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Inilah macam-macam nasakh dari sisi ada atau tidaknya hukum pengganti dan sifat hukum pengganti itu apakah semisal, lebih ringan atau lebih berat.
WalLâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]