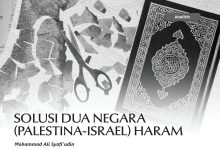Membangun Kemandirian Ekonomi Dunia islam
Dunia Islam, yang mencakup lebih dari 50 negara dengan populasi sekitar 1,9 miliar jiwa, memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, serta jumlah penduduk usia produktif yang signifikan menjadikan Dunia Islam sebagai aset penting dalam sistem ekonomi dunia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud akibat berbagai tantangan struktural dan historis, seperti ketergantungan pada ekspor komoditas, instabilitas politik, ego sektoral, serta dominasi kekuatan asing dalam kebijakan ekonomi (World Bank, 2022).
Dalam lintasan sejarah, Dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban global selama masa keemasan Islam (abad ke-7 hingga ke-14). Saat itu kota-kota seperti Baghdad dan Kordoba memimpin dalam ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi dan seni. Kontribusi pemikir Muslim seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina tidak hanya membentuk fondasi ilmu modern, tetapi juga memperkaya peradaban manusia secara luas (Saliba, 2007). Sayangnya, kejayaan ini tidak berlanjut ke era modern. Saat ini, banyak negeri Muslim menghadapi stagnasi dalam bidang inovasi dan teknologi, yang berdampak langsung pada lemahnya daya saing ekonomi dan ketergantungan terhadap produk serta teknologi asing (UNESCO, 2022).
Warisan kolonialisme Barat juga meninggalkan dampak jangka panjang. Penjajahan tidak hanya merusak struktur ekonomi lokal, tetapi juga menanamkan pola ketergantungan terhadap modal, teknologi dan pasar dari negara maju. Ketergantungan ini menghambat kemandirian ekonomi dan membatasi ruang gerak negara-negara Muslim dalam kancah global (Stiglitz, 2002).
Oleh karena itu, membangun kemandirian ekonomi Dunia Islam menjadi agenda strategis untuk membebaskan umat dari ketergantungan struktural. Upaya ini membutuhkan revitalisasi ilmu pengetahuan, integrasi ekonomi intra-negeri Muslim, serta keberanian politik untuk menciptakan sistem ekonomi yang berdaulat dan berkelanjutan.
Potensi Ekonomi Dunia Islam
Dunia Islam telah lama menjadi objek pertarungan ekonomi global karena berbagai faktor strategisnya. Kawasan-kawasan berpenduduk mayoritas Muslim seperti Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara dan Afrika Utara memiliki posisi geografis yang penting serta kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, terutama minyak dan gas. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak dan Qatar, misalnya, menguasai sebagian besar cadangan energi dunia. Negeri Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memproduksi 63% minyak mentah dunia dan 62% gas alam dunia (Al Hasyim, 2025). Indonesia, sebagai anggota OKI, juga memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Beberapa negara OKI juga memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang besar.
Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait dan Uni Emirat Arab saja memiliki lebih dari 700 miliar barel cadangan minyak. Di sektor gas alam, Iran, Qatar dan Turkmenistan menyumbang lebih dari 30% cadangan gas global. Lapangan gas terbesar dunia, South Pars/North Dome, terletak di wilayah Iran dan Qatar. Energi fosil ini bukan hanya menopang pertumbuhan ekonomi domestik negara-negara tersebut, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap stabilitas energi global.
Kekayaan energi ini menjadikan Dunia Islam tersebut tidak hanya vital secara ekonomi, tetapi juga menjadi ajang perebutan kepentingan oleh kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa Barat. Invasi militer, embargo ekonomi, hingga kontrak bisnis yang timpang kerap menjadi alat kontrol terhadap Dunia Islam ini.
Selain kaya akan energi, Dunia Islam juga sangat strategis secara geografis. Negara-negara Muslim menguasai jalur-jalur laut penting dalam perdagangan global. Selat Hormuz yang terletak di antara Iran dan Oman menjadi jalur vital yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak setiap hari, atau sekitar 30% dari total ekspor minyak dunia menurut U.S. Energy Information Administration (EIA, 2021). Di sisi barat, Terusan Suez di Mesir yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah, dilalui sekitar 12% dari perdagangan maritim global. Di Asia Tenggara, Selat Malaka yang dilalui oleh kapal-kapal dari dan menuju Cina, Jepang dan Asia Timur lainnya menjadi jalur strategis yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia. Semua ini menjadikan Dunia Islam sebagai penjaga lalu-lintas energi dan perdagangan dunia.
Sumberdaya laut juga menjadi kekuatan ekonomi besar bagi Dunia Islam. Negara-negara seperti Indonesia, Maroko, Oman dan Somalia memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Indonesia sendiri, menurut FAO dalam laporan State of World Fisheries and Aquaculture 2022, merupakan produsen ikan tangkap dan budidaya terbesar kedua di dunia. Selain perikanan, kekayaan hayati laut, energi laut seperti arus dan pasang surut, serta potensi pariwisata bahari belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian besar negara-negara Muslim. Potensi ini dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi dan solusi atas ketahanan pangan pada masa depan.
Di tengah tren transisi energi global, potensi energi terbarukan di Dunia Islam juga sangat menjanjikan. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir dan Maroko memiliki paparan sinar matahari yang sangat tinggi. Ini menjadikan negara-negara tersebut cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Wilayah pesisir seperti Maroko dan Pakistan juga sangat potensial untuk energi angin. Indonesia menyimpan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan potensi mencapai 28.000 MW menurut International Renewable Energy Agency (IRENA, 2023). Selain itu, wilayah Asia Tengah dan Selatan seperti Turki, Uzbekistan dan Bangladesh memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hidroelektrik.
Secara keseluruhan, keunggulan geografis Dunia Islam tidak hanya mendukung ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang integrasi ekonomi regional. Kawasan ini menghubungkan tiga benua (Asia, Afrika dan Eropa). Ini menjadikan Dunia Islam sangat strategis sekaligus menjadikan koridor alami bagi perdagangan dan logistik.
Menuju Keadilan dan Kemandirian Ekonomi
Di tengah ketimpangan global yang semakin menganga (saat segelintir elit menguasai mayoritas sumber daya, sementara miliaran lainnya hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan), sistem ekonomi dunia saat ini menunjukkan kegagalannya dalam mewujudkan keadilan (Piketty, 2014; Oxfam, 2023). Sistem kapitalisme telah memberikan ruang tak terbatas bagi akumulasi kekayaan melalui mekanisme pasar bebas, privatisasi dan liberalisasi ekonomi. Namun, kapitalisme gagal menjamin distribusi kekayaan yang merata dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan umat manusia.
Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan (al-‘adl). Keadilan dalam Islam bukan hanya bersifat moral, melainkan merupakan pilar dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam memandang bahwa kepemilikan harta bukanlah hak absolut individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab (Chapra, 2000). Oleh karena itu, mekanisme distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian. Islam menolak sistem yang membuat harta beredar hanya di sekelompok orang kaya (QS al-Hasyr [59]:7). Islam menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan secara merata dalam masyarakat.
Distribusi kekayaan dalam sistem Islam dilakukan melalui instrumen-instrumen spesifik seperti zakat, sedekah, waris dan larangan menimbun harta (kanz). Zakat, misalnya, tidak hanya menjadi ibadah spiritual, tetapi juga merupakan mekanisme fiskal yang mengalirkan kekayaan dari kelompok kaya kepada fakir miskin. Negara bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan zakat melalui Baitul Mal, lembaga keuangan publik dalam Negara Islam (Kahf, 1995). Dengan demikian, peran negara sangat signifikan dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil.
Negara dalam sistem ekonomi Islam bukanlah aktor pasif atau sekadar regulator seperti dalam sistem kapitalisme. Negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu—pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini ditegaskan oleh Al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam (2001). Beliau menyebut bahwa Negara Islam wajib mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan rakyat dan mencegah pemusatan kekayaan di tangan segelintir individu atau korporasi.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara memegang peran sentral sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat. Al-Maliki (2001) menyatakan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam pembangunan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perdagangan dan industri. Keterlibatan negara dalam sektor-sektor ini menjadi sangat penting. Ini karena negara berpotensi menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang selama ini menjadi ciri khas sistem kapitalisme.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Salah satu pilar utama yang menjadi fokus perhatian dalam kerangka ekonomi Islam adalah pengembangan sektor industri. Industri dipandang sebagai fondasi ekonomi modern yang mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus bersaing di pasar internasional. Al-Maliki (2001) menjelaskan bahwa pembangunan industri harus dilakukan secara efisien dan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup keadilan dalam distribusi hasil produksi, penguatan sektor riil serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan demikian, pengembangan industri bukan hanya tentang pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal memastikan keberlanjutan dan pemerataan ekonomi.
Namun, dalam konteks global saat ini, sistem kapitalisme yang dominan telah memperlihatkan sisi gelapnya melalui praktik eksploitasi ekonomi yang terjadi akibat liberalisasi pasar dan privatisasi sumber daya alam. Ketika kepemilikan dan pengelolaan aset-aset strategis seperti minyak, gas, air dan hutan diserahkan kepada individu atau korporasi, maka yang terjadi adalah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara masyarakat luas justru kehilangan akses terhadap hak-hak ekonominya. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang menempatkan sumber daya strategis sebagai milik umum. An-Nabhani (2004) dalam An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm menegaskan bahwa negara berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasil dari sumber daya tersebut demi kemaslahatan umat. Prinsip kepemilikan umum ini bertujuan mencegah eksploitasi serta menjamin distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.
Selain menolak privatisasi sumber daya publik, sistem ekonomi Islam juga memiliki mekanisme protektif lain untuk mencegah ketimpangan, yaitu dengan melarang praktik riba. Dalam pandangan Islam, riba merupakan bentuk eksploitasi keuangan yang menciptakan ketidakadilan struktural serta memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara negara maju dan negara terbelakang.. Dalam konteks negara, banyak negara maju memberikan pinjaman, namun harus satu paket dengan bunga utangnya. Baik secara langsung ataupun menggunakan kaki tangannya, seperti IMF dan World Bank. Pada akhirnya banyak negeri Muslim yang terperangkap dengan jebakan utang luar negeri. Siddiqi (2004) menjelaskan bahwa sistem bunga dalam kapitalisme tidak hanya membebani negara berkembang dengan utang yang terus menumpuk, tetapi juga menjadi penyebab utama berbagai krisis keuangan global. Sebagai gantinya, Islam mendorong bentuk-bentuk transaksi berbasis kerjasama dan pembagian risiko, seperti mudhârabah, yang tidak hanya mendorong aktivitas produktif, tetapi juga membangun kepercayaan dan kemandirian ekonomi.
Dengan perpaduan antara peran aktif negara, pengelolaan sumber daya publik secara kolektif, pengembangan industri berlandaskan syariah, serta pelarangan praktik riba, sistem ekonomi Islam menawarkan suatu tatanan yang tidak hanya adil dan seimbang tetapi juga lebih manusiawi. Sistem ini berbeda secara fundamental dari kapitalisme maupun sosialisme. Pasalnya, sistem ini berakar pada nilai-nilai spiritual dan ideologis yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara individu, masyarakat, dan negara dalam kerangka penghambaan kepada Allah SWT.
Sistem moneter Islam juga berbasis pada mata uang yang memiliki nilai intrinsik seperti dinar emas dan dirham perak. Ini menghindari inflasi buatan dan manipulasi nilai tukar yang kerap terjadi dalam sistem fiat money saat ini (Meera & Larbani, 2009). Dengan sistem ini, kestabilan harga dan daya beli dapat lebih terjamin, serta mencegah dominasi mata uang negara kuat atas negara-negara lemah (Utomo et. al., 2023).
Penerapan sistem ekonomi Islam untuk kemandirian ekonomi bukanlah sekadar utopia. Sejarah mencatat bagaimana Negara Islam (khilafah Islam) mampu mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang luar biasa. Kota-kota seperti Baghdad, Kordoba dan Kairo pernah menjadi pusat peradaban yang makmur dan maju secara ekonomi (Lapidus, 2002). Kesejahteraan bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga oleh komunitas non-Muslim yang hidup dalam Negara Khilafah.
Pada masa kini, meskipun sistem ekonomi Islam belum diterapkan secara menyeluruh oleh negara manapun, prinsip-prinsipnya telah mulai diadopsi melalui sistem keuangan syariah yang berkembang di berbagai negara. Namun, tanpa penerapan sistem secara menyeluruh oleh negara, prinsip-prinsip tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal (Marlina et al., 2019). Sistem parsial hanya akan menjadikan ekonomi Islam sebagai pelengkap dari sistem kapitalis, bukan sebagai alternatif menyeluruh (Asutay, 2007).
Dengan demikian, sudah saatnya Dunia Islam—dengan seluruh potensi sumber daya dan warisan intelektualnya—bangkit dan mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.
Penutup
Membangun ekonomi Dunia Islam yang mandiri, kuat dan berkeadilan bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, Dunia Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan perekonomian yang stabil dan kokoh. Untuk mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi global, Dunia Islam membutuhkan satu kesatuan yang mampu menghimpun potensi tersebut. Diperlukan suatu kepemimpinan global yang kuat, yang mampu tampil di kancah global menantang kekuatan kapitalisme Barat. Dengan itu Dunia Islam menjadi pemain utama dalam sistem ekonomi global yang mandiri dan lebih berkeadilan.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. [Dr. Julian ; [Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)]]
Referensi:
Al-Maliki, A. (2001). Politik Ekonomi Islam. Hizbut Tahrir.
Al Hasyim, M. M. ( 2025) Organisasi Kerja Sama Islam (Oki) dan Transisi Energi di Tengah Kompleksitas Kawasan Timur Tengah. Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (Jisip-Unja) Vol. 9 No. 1. pp 38-48
An-Nabhani, T. (2004). Nizamul Iqtishadi Fil Islam. Al-Khilafah Publications.
Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus. IIUM Journal of Economics and Management.
Chapra, M. Umer. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. The Islamic Foundation.
EIA. (2021). World Oil Transit Chokepoints. https://www.eia.gov
FAO. (2022). State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). https://www.fao.org
IRENA. (2023). Renewable Capacity Statistics. https://www.irena.org
Kahf, M. (1995). The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Islamic Research and Training Institute.
Lapidus, I. M. (2002). A History of Islamic Societies. Cambridge University Press.
Marlina, R., Juliana, J., Adila, N. A., & Robbani, M. B. (2019). Islamic political economy: Critical review of economic policy in Indonesia. Review of Islamic Economics and Finance, 2(1), 47-55.
Meera, A. K. M., & Larbani, M. (2009). The Gold Dinar and Barter Trade System. Humanomics.
Oxfam. (2023). Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality.
Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
Saliba, G. (2007). Islamic Science and the Making of the European Renaissance. MIT Press.
Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition. Islamic Research and Training Institute.
Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company.
UNESCO Institute for Statistics. (2022). Science, Technology and Innovation Data.
Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., Juliana, J., & Anggrismono, A. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. Islamic Research, 6(1), 63-68.
World Bank. (2022). World Development Indicators. https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/