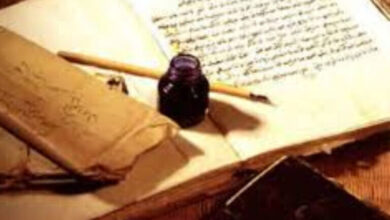Bayân al-Mujmal
Di dalam al-Quran dan as-Sunnah ada nas-nas yang mujmal. Dalil al-mujmal itu, karena ketidakjelasan dalâlah-nya atau karena mengandung lebih dari satu dalâlah atau makna dan tidak ada keistimewaan yang satu atas yang lain, maka hukumnya belum dapat diamalkan. Padahal asal pada dalil itu adalah diamalkan, bukan diabaikan. Maka dari itu perlu dalil yang menjelaskan dalil yang al-mujmal itu.
Jadi semua yang al-mujmal memerlukan al-bayân (penjelasan). Qadhi Abu Ya’la al-Fara‘ (w. 458 H) menjelaskan di dalam Al-‘Iddah fî Ushûl al-Fiqhi, “Adapun apa yang memerlukan al-bayân adalah semua lafal yang tidak mungkin dilaksanakan hukumnya (tanpa al-bayân). Misal firman Allah SWT [ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ] dan [ وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ ], juga sabda Rasul saw:
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, “Tidak ada Tuhan kecuali Allah.” Jika mereka mengatakan demikian maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Adapun yang mungkin dijalankan menurut lahiriah dan hakikatnya tidaklah memerlukan al-bayân. Sebaliknya, jika yang diinginkan oleh yang menyeru adalah sebagian yang dikandungnya atau bukan hakikatnya maka perlu penjelasan yang diinginkan itu. Misalnya firman Allah SWT [ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ ] dan [ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ] dan [ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ]. Lafal-lafal ini maknanya dapat dipahami (secara langsung) dan jelas sehingga tidak memerlukan al-bayân”.
Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahulLâh menyatakan di dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah Jilid 3: “al-bayân adalah dalil yang menjelaskan al-mujmal”. Al-Bayân adalah dalil yang telah jelas dalâlah atau maknanya, yang menjelaskan dalil yang al-mujmal.
Penjelasan (bayân) al-mujmal ini tidak harus menghasilkan dalâlah yang qath’i. Demikian seperti dijelaskan oleh al-‘Abdari yang dikutip oleh az-Zarkasyi di dalam Bahru al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqhi: “…Yang menjadi pokok al-bayân adalah dalil, yakni dalil yang telah jelas dalâlah atau maknanya sehingga dapat memberikan penjelasan atas kesamaran atau ketidakjelasan dalil lainnya dan menghasilkan al-‘ilmu (keyakinan) atau dugaan kuat atas dalâlah atau maknanya.”
Bayân al-mujmal itu, karena merupakan penjelasan atas dalil yang al-mujmal, maka ia harus berupa dalil juga. Dalil yang al-mujmal itu hanya ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Adapun di dalam al-Ijmâ’ dan al-Qiyâs maka tidak ada yang mujmal. Bayân al-mujmal itu terjadi dengan al-Quran, as-Sunnah mutawaatir dan ahad, al-Ijmâ‘ dan al-Qiyâs. Qadhi Abu Ya’la (w. 458 H) menyatakan, “Adapun apa yang dengannya terjadi al-bayân adalah al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijmâ‘ dan al-Qiyâs.”
Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, “Al-Bayân dapat berupa ucapan dari Allah dan Rasul saw., juga berupa perbuatan dari Rasul saw. Contoh al-bayân dari Allah adalah firman-Nya [ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ] sampai akhir merupakan penjelasan untuk firman-Nya SWT [ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ]. Contoh al-bayân berupa ucapan dari Rasul saw adalah apa yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi:
Rasulullah saw. tidak memfardhukan zakat kecuali pada sepuluh sesuatu: unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, jelay, kurma, kismis dan as-sultu (salah satu jenis jelay).
Itu adalah penjelasan untuk ayat tentang kefardhuan zakat. Contoh al-bayân berupa perbuatan dari Rasul saw. adalah apa yang diriwayatkan dari beliau yang memberitahukan shalat dan haji melalui perbuatan beliau. Beliau bersabda: « صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ » (Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat) (HR al-Bukhari); « أَلَا فَخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ » (Ingatlah, ambillah dariku manasik haji kalian) (HR Ahmad). Perbuatan beliau untuk shalat itu merupakan penjelasan untuk firman Allah SWT [ وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ ] (Dirikanlah shalat oleh kalian). Perbuatan beliau untuk haji merupakan penjelasan untuk firman-Nya SWT [ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ] (Mengerjakan ibdah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah) (TQS Ali Imran [3]: 97).
Al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H) menyatakan di dalam Al-Faqîh wa al-Mutafaqqih, “Al-Bayân terjadi dengan ucapan, mafhûm ucapan (mafhûm al-muwâfaqah dan mafhûm al-mukhâlafah, pen.), perbuatan Rasul, al-iqrâr (taqrîr-persetujuan Rasul), isyarat dari Rasul, tulisan dari Rasul dan dengan qiyas.”
Menurut Qadhi Abu Ya’la al-Fara (w. 458 H) di dalam Al-‘Iddah fî Ushûl al-Fiqhi, bayân al-mujmal itu bisa datang dari Allah dalam bentuk ucapan dan tulisan; bisa dating dari Rasul dengan ucapan, tulisan, perbuatan, isyarat, iqrâr (persetujuan) atas perbuatan yang beliau saksikan dilakukan oleh pelakunya dan tidak beliau ingkari. Bayân juga dengan ad-dalâlah wa at-tanbîh terhadap hukum tanpa nas atau, dalam istilah ulama lainnya, yakni dengan al-qiyâs. Bayân juga terjadi dengan Ijmak.
Menurut Abu al-Muzhaffar as-Sam’ani (w. 489 H) di dalam Qawâti’u al-Adillah fî al-Ushûl, bayân al-mujmal terjadi dalam enam wajah (bentuk). Pertama, dengan ucapan. Ini yang paling besar dan tegas seperti penjelasan nishaab zakat dan sabda Rasul saw. « وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا » (Hukuman potong tangan itu berlaku pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih).
Kedua, dengan perbuatan seperti sabda Rasul saw. « صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ » (Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat) (HR al-Bukhari); « أَلَا فَخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ » (Ingatlah, ambillah dariku manasik haji kalian) (HR Ahmad).
Ketiga, bayân dengan tulisan seperti penjelasan Rasul saw. untuk diyat gigi dan diyat anggota badan dengan tulisan. Demikian juga zakat.
Keempat, bayân rasul saw. dengan isyarat semisal sabda beliau:
“Satu bulan begini, begini dan begini, yakni yakni 30 hari.” Kemudian beliau mengulangi isyarat tiga kali itu. Lalu beliau menahan ibu jari beliau pada yang ketiga jadi 29 hari.
Kelima, bayân beliau dengan tafsir (penjelasan) dan itu adalah makna dan ‘illat yang beliau informasikan atas penjelasan hukum seperti sabda beliau tentang jual-beli ruthab (kurma basah) dengan kurma « أَيَنْقُصَ إِذَا يَبِسَ » (Apakah ruthab berkurang jika mengering); juga seperti sabda beliau tentang orang berpuasa yang mencium istrinya « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ » (Bagaimana menurut pandanganmu andai kamu berkumur?).
Keenam, dikhususkan oleh ulama dengan penjelasannya dari ijtihad mereka. Hal itu adalah apa yang di dalamnya dikedepankan lima bentuk tersebut jika ijtihad itu mengantarkan padanya dari salah satu di antara bentuknya. Adakalanya dari pokok yang dengannya cabang ini mu’tabar dan adakalanya dari jalan sinyal (amarah) yang menunjukkannya.
Hal senada disampaikan oleh Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam Al-Mahshûl, Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) di dalam Al-Mu’tamad fî Ushûl al-Fiqhi, al-Isnawi (w. 772 H ) di dalam Nihâyah as-Sûl, Ibnu Qudamah (w. 620 H ) di dalam Rawdah an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir, dan lainnya.
Tentang bayân dengan perbuatan Rasul saw., Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di al-Mahshûl menjelaskan, “Ketahuilah bahwa tidak diketahui keberadaan perbuatan sebagai bayân untuk al-mujmal kecuali dengan salah satu dari tiga: Pertama, hal itu diketahui dengan adh-dharûrah dari maksudnya. Kedua, diketahui dengan dalil lafzhi, yaitu Rasul saw. bersabda, “perbuatan ini adalah penjelasan untuk al-mujmal ini”; atau beliau mengatakan ucapan-ucapan yang meniscayakan hal itu dari keseluruhannya. Ketiga, dengan dalil ‘aqli, yaitu disebutkan al-mujmal, lalu pada waktu perlu dilaksanakan, beliau melakukan perbuatan yang layak menjadi bayân untuknya dan beliau tidak melakukan sesuatu yang lain, maka diketahui bahwa perbuatan itu merupakan bayân untuk al-mujmal tersebut. Jika tidak maka terjadi penundaan bayân dari waktu diperlukan dan bahwa itu tidak boleh.”
Jika terjadi bayân berupa sabda dan perbuatan Rasul saw., maka, seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Amidi di dalam Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm dan al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah Jilid 3: Adakalanya keduanya sama dalâlah-nya terhadap hukum dan adakalanya berbeda. Jika dalâlah hukumnya sama maka yang lebih dulu merupakan bayan, baik berupa sabda atau perbuatan, karena tercapainya maksud dengannya; dan yang kedua adalah penegasan (ta`kîd). Jika berbeda dalam dalâlah hukumnya, seperti diriwayatkan bahwa setelah ayat tentang haji, Rasul saw. bersabda: « مَنْ قَرَنَ حَجًّا إِلَى عُمْرَةٍ فَلْيَطُفْ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا » (Siapa yang mengaitkan haji ke umrah maka hendaklah thawaf sekali dan sa’i sekali) (HR Ahmad). Juga diriwayat dari Rasul saw.: « كَانَ قَارِنًا فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ » (Beliau mengaitkan haji ke umrah dan beliau thawaf dua kali dan sa’i dua kali) (HR ad-Daraquthni). Dalam hal ini perlu diperhatikan: Jika tidak diketahui mana yang lebih dulu, sabda atau perbuatan beliau, maka diambil sabda beliau. Hal itu karena ucapan menunjukkan secara langsung keberadaannya sebagai bayân. Berbeda dengan perbuatan, yang menunjukkannya dengan perantaraan (yakni dengan tiga hal yang dijelaskan oleh Fakhruddin ar-Razi di atas). Maka dari itu, diperkirakan ucapan sebagai yang lebih dulu dan dibawa pada pemahaman bahwa thawaf dan sa’i yang kedua adalah mandûb (sunnah).
Jika diketahui yang lebih dulu, yakni sabda beliau, maka thawaf dan sa’i yang kedua tidak wajib. Lalu perbuatan Nabi saw. wajib dibawa pada hukum mandûb. Jika diketahui yang lebih dulu adalah perbuatan maka sabda Nabi saw. menjadi me-naskh kewajiban thawaf dan sa’i kedua yang ditunjukkan oleh perbuatan itu; atau dibawa pemahamannya bahwa perbuatan Rasul saw. sebagai bayân kewajiban thawaf dan sa’i kedua bagi beliau, tetapi tidak wajib bagi umat beliau.
Adapun bayân melalui ijtihad, dalam istilah Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah di dalam Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl, disebut dengan al-bayân al-mustanbath. Misalnya, firman Allah SWT [ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ] bahwa dalâlah al-wâwu pada wa ar-râsikhûna bersifat mujmal antara untuk al-‘athaf atau al-isti’nâf sehingga perlu bayân yang me-râjih-kan salah satunya. Dengan intinbâth itu menjadi jelas bahwa tambahan sifat pada ilmu dengan ar-râsikhûna pasti punya relevansi. Jika al-wâwu untuk al-isti’nâf, jadilah kalimat “wa ar-râsikhûna fî al-‘ilmi” merupakan kalimat baru. Dengan demikian tambahan sifat ar-rusûkh fî al-‘ilm (mendalam ilmunya) itu adalah untuk iman dan ini tidak relevan. Sebabnya, untuk beriman tidak diperlukan sifat itu, tetapi cukup ilmu saja. Bahkan akal yang sehat dan lurus sudah cukup untuk beriman.
Adapun jika al-wâwu untuk al-‘athaf maka sifat ar-rusûkh fî al-i’lmi itu untuk mengetahui takwil al-mutasyâbih dan ini relevan. Sebabnya, untuk mengetahui takwil al-mutasyâbih diperlukan ilmu yang mendalam. Dari situ maka yang râjih adalah al-wâwu itu untuk al-‘athaf sehingga waqaf dalam bacaannya adalah setelah wa ar-râsikhûna fî al-‘ilmi, bukan setelah lafal AlLâh.
Selain itu, jika al-wâwu itu untuk al-isti’nâf sehingga waqaf adalah setelah lafal AlLâh, maka maknanya hanya Allah saja yang mengetahui takwil ayat al-mutasyâbih. Ini bertentangan dengan firman Allah SWT lainnya bahwa al-Quran merupakan [ بَيَانٌ لِلنَّاسِ ] (penjelasan untuk manusia) (TQS Ali Imran [3]: 138) dan [ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ] (untuk menjelaskan segala sesuatu) (TQS an-Nahl [16]: 89). Ini meniscayakan semua ayat al-Quran dapat dipahami termasuk ayat al-mutasyâbih. Adapun jika al-wâwu itu untuk al-‘athaf maka maknanya bahwa takwil ayat al-mutasyâbih itu juga diketahui oleh ar-râsikhûna fî al-‘ilmi (orang-orang yang mendalam ilmunya). Ini sesuai dengan firman Allah QS Ali Imran [3]: 138 dan an-Nahl [16]: 89 tersebut.
Inilah contoh bayân dengan ijtihad atau al-bayân al-mustanbath (penjelasan yang di-istinbâth).
WalLâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]