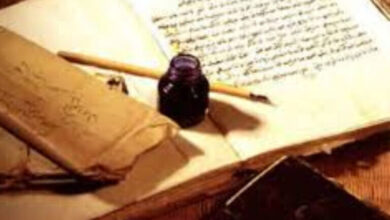Nasakh
An-Naskhu secara bahasa memiliki dua makna: Pertama, bermakna pencabutan (ar-raf’u) atau pembatalan (al-ibthâl) dan penghilangan (al-izâlah). Kedua, bermakna penukilan (an-naqlu) dan perubahan setelah adanya (at-tahwîl ba’da tsubût).
Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam Al-Mushtashfâ fî ‘Ilmi al-Ushûl menyatakan, an-naskhu adalah ungkapan tentang ar-raf’u (pencabutan) dan al-izâlah (penghilangan) dalam ketetapan lisan (bahasa).
Imam Taqiyuddin as-Subki (w. 756 H) di dalam Al-Ibhâj fî Syarhi al-Minhâj menyatakan bahwa an-naskhu secara bahasa disebutkan atas penghilangan (al-izâlah); Nasakhat ar-rîhu atsara al-qadami (Angin itu telah menghapus jejak kaki), yakni: azâlathu (menghilangkannya/menghapusnya). Juga disebutkan atas penukilan (an-naqlu) dan pengubahan (at-tahwîl). Dari situ dikatakan: Nasakhtu al-kitâba (Aku menukil kitab), yakni: naqaltuhu (aku menukilkannya). Itulah makna firman Allah SWT:
Sesungguhnya Kami telah menyuruh untuk menukilkan (mencatat) apa yang telah kalian kerjakan (QS al-Jatsiyah [45]: 29).
Dari situ dikatakan al-munâsakhât, yaitu perpindahan harta dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya.
Menurut Imam Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di dalam Bahru al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqhi, juga Imam asy-Syawkani di dalam Irsyâd al-Fuhûl, dalam Bahasa: an-naskhu disebutkan dan yang diinginkan adalah pembatalan (al-ibthâl) dan penghilangan/penghapusan (al-izâlah)…Juga disebutkan dan yang diinginkan adalah penukilan (an-naqlu) dan pengubahan setelah terbukti ada (at-tahwîl ba’da tsubût). Makna ini yang ada dalam QS al-Jatsiyah [45]: 29.
Adapun secara istilah, para ulama ushul memberikan definisi dan batasan yang sedikit berbeda satu sama lain. Imam al-Ghazali (w. 505 H) menyatakan di dalam Al-Mushtashfâ fî ‘Ilmi al-Ushûl, bahwa an-naskhu adalah: al-khithâbu ad-dâlu ‘alâ irtifâ’i al-hukmi ats-tsâbiti bi al-khithâbi al-mutaqaddim ‘alâ wajh[in] lawlâhu lakâna tsâbit[an] bihi ma’a tarâkhîhi ‘anhu (seruan yang menunjukkan pencabutan hukum yang ditetapkan dengan seruan terdahulu dalam bentuk yang seandainya tidak ada an-naskhu niscaya hukum itu tetap berlaku).
Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam Al-Mahshûl menyatakan, dan lebih utama dikatakan: an-naskhu adalah tharîq[un] syar’iyy[un] yadullu ‘alâ anna mitsla al-hukmi al-ladzî kâna tsâbit[an] bi tharîq[in] syar’iyy[in] lâ yûjadu ba’da dzâlika ma’a tarâkhîhi syar’i ‘anhu ‘alâ wajh[in] lawlâhu lakâna tsâbit[an] (cara syar’i yang menunjukkan bahwa semisal hukum yang dulu pernah berlaku dengan cara syar’i tidak ada lagi setelah itu seiring dengan lebih akhirnya darinya dalam bentuk yang seandainya tidak ada an-naskhu niscaya hukum itu tetap berlaku).
Al-Qadhi al-Baydhawi (w. 785 H) di dalam Minhâju al-Wushûl memberikan definisi an-naskhu dengan: bayânu intihâ‘i hukm[in] syar’iyy[in] mutarâkh[in] (penjelasan tentang berakhirnya hukum syar’i belakangan setelah suatu waktu).
Imam Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di Bahru al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqhi menyatakan, “Yang terpilih bahwa an-naskhu adalah raf’u al-hukmi asy-syar’iy bi khithâb[in] (pengangkatan [pencabutan] hukum syar’i melalui suatu seruan). Di antara ulama ada yang menambah batasan at-tarâkhiy (lebih belakangan setelah jangka waktu) agar keluar (dari definisi an-naskhu) itu apa yang bersambung dengan hukum tersebut seperti pengecualian, syarat dan sifat, sebab itu adalah penjelasan (bayân) untuk ujung hukum tersebut dan tidak disebut naskhu karena kemustahilan akhir ucapan menghalangi awalnya.”
Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) di dalam Rawdhah an-Nâzhir wa Jannatu al-Munâzhir menjelaskan batasan an-naskhu yakni: raf’u al-hukmi ats-tsâbiti bi khithâb[in] mutaqaddim bi khithâb[in] mutarâkh[in] ‘anhu (pencabutan hukum yang ditetapkan dengan suatu seruan yang lebih dulu dengan seruan yang lebih akhir).
Imam Ibnu al-Hajib (w. 646 H) di dalam Mukhtashar Muntahâ as-Sûl (Mukhtashar Ibni al-Hâjib) menyatakan batasan yang mirip bahwa an-naskhu adalah raf’u hukm[in] syar’iyy[in] bi dalîl[in] syar’iyy[in] muta‘akhir[in] (pencabutan [pembatalan] hukum syar’i dengan dalil syar’i yang lebih akhir).
Imam al-Amidi (w. 631) di dalam Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm menjelaskan bahwa meski demikian, yang terpilih dalam batasan an-naskhu dikatakan: an-naskhu adalah: khithâb asy-Syâri’i al-mâni’i min istimrâri mâ tsabata min hukmi khithâb[in] syar’iyy[in] sâbiq[in] (seuran Asy-Syâri’ yang menghalangi keberlanjutan hukum yang sebelumny telah ditetapkan oleh seruan syar’i terdahulu).
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah Jilid 3 menyatakan: an-naskhu adalah ibthâlu al-hukmi al-mustafâd min nashsh[in] sâbiq[in] bi nashsh[in] lâhiq[in] (pembatalan hukum yang dipahami dari nas yang lebih dulu dengan nas yang lebih akhir). Rasul saw., misalnya, bersabda: « كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلَا فَزُوْرُوْهَا » (Dulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Sekarang, berziarahlah ke kubur kalian).” (HR al-Hakim). Dikatakan juga: an-naskhu adalah khithâbu asy-Syâri’i al-mâni’i min istimrâri mâ tsabata min hukmi khithâb[in] syar’iyy[in] sâbiq[in] (seruan Asy-Syâri’ yang menghalangi keberlanjutan hukum yang pernah ditetapkan oleh seruan syar’i yang terdahulu).
Dari batasan-batasan dan definisi an-naskhu yang dijelaskan para ulama ushul, jelas bahwa an-naskhu itu: Pertama, hakikatnya merupakan pencabutan atau pembatalan (ar-raf’u atau al-ibthâl) hukum syariah yang telah ditetapkan oleh seruan Asy-Syâri’ yang lebih dulu. Imam Badruddin az-Zarkasyi menjelaskan di dalam Bahru al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh, “Apa yang telah kami sebutkan, bahwa keberadaan an-naskhu sebagai pencabutan (raf’un), adalah pilihan pendapat Ash-Shairafi, al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, Syaikh Abu Ishaq asy-Syirazi, al-Ghazali, al-Amidi, Ibnu al-Hajib, dan Ibnu al-Anbari, dan itu adalah yang terpilih (al-mukhtâr)”. Pencabutan atau pembatalan ini bermakna penghentian keberlanjutan pemberlakuan hukum itu.
Kedua, pencabutan atau pembatalan itu melalui khithâb asy-Syâri’ yang lebih akhir. Ini menjelaskan bahwa pemberhentian pemberlakuan hukum karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan untuk hukum itu, atau karena hilangnya sebab atau ‘illat-nya, bukanlah an-naskhu.
Ketiga, khithaab yang me-naskh harus lebih akhir. Artinya, ada jeda waktu antara khithaab yang me-nasakh dengan khithaab yang hukumnya di-nasakh. Inilah makna mutarâkhiy atau muta‘akhir atau ma’a at-tarâkhiy dalam penjelasan para ulama ushul. Dengan batasan ini, jika khithaab-nya itu bersambung maka bukan an-naskhu melainkan bayân dalam bentuk takhshîsh atau taqyîd seperti al-istitsnâ‘ (pengecualian), asy-syarthu (syarat), al-ghâyah (ujung), dsb.
Dalil an-Naskhu
Dalil kebolehan an-naskhu adalah al-Quran, Ijmak Sahabat dan terjadinya an-naskhu secara riil di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Dalil berupa al-Quran, Allah SWT berfirman:
Ayat mana saja yang Kami hapus atau Kami biarkan tidak dihapus, Kami datangkan yang lebih baik dari ayat tersebut atau yang sebanding dengannya (QS al-Baqarah [2]: 106).
Menurut Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah di dalam Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr, maknanya adalah ayat mana saja yang kami nasakh atau kami biarkan tanpa nasakh.
Allah SWT juga berfirman:
Jika Kami meletakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya… (QS an-Nahl [16]: 101).
Imam az-Zamakhsyari (w. 538 H) di dalam tafsirnya Al-Kasyâf menjelaskan, “Penggantian ayat pada posisi ayat lainnya adalah an-naskhu. Allah SWT me-nasakh syariat-syariat dengan syariat lainnya sebab itu adalah kemaslahatan. Allah Mahatahu atas kemaslahatan dan kemafsadatan sehingga Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki dan me-nasakh apa yang Dia kehendaki dengan hikmah-Nya.”
Adapun Ijmak Shahabat, telah terakadkan Ijmak Sahabat bahwa syariah Nabi Muhammad saw. me-nasakh semua syariah terdahulu. Juga telah terakadkan Ijmak mereka atas pe-nasakh-an kewajiban menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan menghadap ke arah Baitullah al-Ka’bah; juga pe-nasakh-an kewajiban wasiat harta untuk ibu-bapak dan kerabat dengan ayat-ayat waris, pe-nasakh-an kewajiban Puasa Asyura’ dengan Puasa Ramadhan; kewajiban bersedekah sebelum berbicara berdua dengan Rasul di-nasakh yakni dibatalkan, dan lainnya. Semua itu telah disepakati oleh para Sahabat atas pe-nasakh-annya sehingga terakadkan ijmak mereka atas an-naskhu dan itu merupakan dalil syar’i atas an-naskhu.
Adapun terjadinya an-naskhu secara riil, maka Ijmak Sahabat atas peristiwa-peristwa yang di situ terjadi nasakh merupakan dalil atas terjadinya nasakh secara riil. Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah shalat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan di Madinah. Kemudian beliau sangat ingin dan berharap ada pengalihan kiblat ke arah Baitullah al-Ka’bah. Lalu diturunkan QS al-Baqarah [2]: 144. Dengan demikian hukum menghadap kiblat ke Baitul Maqdis di-nasakh dan diganti ke arah Baitullah al-Ka’bah. Masih banyak nasakh lainnya di dalam al-Quran.
Juga ada pe-nasakh-an di dalam as-Sunnah. Abdullah bin Buraidah menuturkan dari bapaknya bahwa Rasul saw. pernah bersabda:
Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah ke sana. Aku pernah melarang kalian daging kurban lebih dari tiga hari. Sekarang simpanlah yang kalian perlukan. Aku pernah melarang kalian minum an-nabidz kecuali dalam kantong air. Sekarang minumlah dalam kantong air semuanya (semua minuman), tetapi jangan kalian minum yang memabukkan (HR Muslim).
Masih banyak hukum-hukum lainnya yang di situ terjadi nasakh secara riil yang dijelaskan di as-Sunnah. Semua nasakh yang terjadi di dalam al-Quran dan as-Sunnah itu merupakan dalil adanya an-naskhu. Terjadinya an-naskhu secara riil merupakan dalil kebolehan an-naskhu dan dalial adanya an-naskhu. Jadi semua itu merupakan dalil atas an-naskhu.
WalLâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]